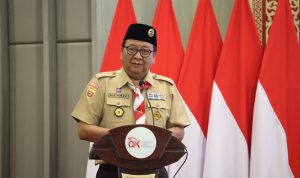MUARAENIM | KabarSriwijaya.NET — Malam di Muaraenim tidak pernah benar-benar sunyi. Gemuruh knalpot liar, derap sepeda motor yang memecah gelap selepas isyak adalah suara-suara umum di kota kecil tambang itu. Namun di pojok yang tenang, jauh dari dentum knalpot dan gemerlap layar gawai, sekelompok anak muda sedang menyalakan lentera kecil. Bukan lentera biasa, tapi lentera gagasan dan cita-cita, yang menyala dari masjid dan ruang belajar Pondok Pesantren Laa Roiba.
Adalah Jastin Samuel dan Lazirin Syafa, dua nama remaja yang terpilih dalam dua forum berbeda di pekan yang sama. Mereka bukan aktivis politik, bukan pula bintang media sosial.

Tapi dari tangan mereka, organisasi dan teater di pesantren ini akan berjalan satu tahun ke depan. Di saat remaja lain sibuk menjadi avatar di dunia maya, mereka memilih menjadi manusia nyata, di panggung nyata—yang kadang remang dan tak sempurna.
Kertas Suara dan Kalimat Panggung
Sabtu malam itu, aula kecil Pondok bergemuruh oleh suara ratusan santri. OSLA, singkatan dari Organisasi Santri Laa Roiba, menggelar musyawarah besar. Di tangan para santri, kertas suara dibagikan. Suara dibacakan dalam suasana hikmat. Dari empat kandidat, Jastin Samuel muncul sebagai pemenang: 71 suara yang memilihnya sebagai Ketua OSLA 2025–2026.
Tiga malam sebelumnya, di Masjid Julaibib, suasana tak kalah dramatis. Bukan musyawarah politik, melainkan panggung teater yang sedang dicari nahkodanya.

Di lantai masjid itu, para anggota Teater Batu Hitam berdiri satu per satu, memaparkan visi mereka dengan bahasa sederhana, kadang melantur, kadang menggelikan. Tapi di sanalah letak keindahannya: demokrasi yang polos, dan ketulusan yang mentah.
Dari dua belas kandidat, Lazirin Syafa menang tipis. Enam suara menghantarkannya jadi Ketua Teater Batu Hitam yang baru. Bersama beberapa nama lain, mereka akan membentuk tim formatur, menyusun program, menulis anggaran dasar, dan mungkin, naskah pertunjukan baru. Teater ini bukan panggung hampa; ia lahir dari rahim sejarah. Tahun 2005, KH Taufik Hidayat menggagasnya di Masjid Jamik PTBA, kini ia kembali dihidupkan di bawah naungan pesantren.
Dua Jalan, Satu Tujuan
Jastin dan Lazirin tidak sedang mengejar sorotan, bukan pula tepuk tangan. Tapi dari mereka, tampak jelas wajah generasi baru santri—yang berpikir, berani berbicara, dan berlatih memimpin. “Jangan hangat-hangat tai ayam,” kata Ustadz Wartawan, Wakil Pimpinan Pondok, memberi wejangan keras tapi penuh makna pada Jastin dan rekan-rekannya. Pesan agar tak semangat sesaat, lalu redup seperti bara lupa dikipas.
Sementara di lingkaran teater, Ustadz Imron Supriyadi, pelatih sekaligus pegiat seni, memberi napas panjang pada dunia lakon. “Teater bukan sekadar panggung dan dialog. Ia adalah denyut zaman, suara luka yang diberi tempat,” katanya pada para santri. Ia tak sekadar melatih akting, tapi menghidupkan kesadaran sosial: bahwa lakon bisa menjadi alat untuk memahami manusia.
Pesantren dan Masa Depan
Di tengah riuh zaman, Laa Roiba menunjukkan bahwa pondok bukan hanya tempat menghafal kitab. Di sini, demokrasi kecil tumbuh di balik tembok mushola. Teater menemukan napasnya di sela tilawah dan halaqoh. Dan di tangan santri Gen-Z, organisasi bukan sekadar formalitas, tapi ladang latihan menjadi manusia yang utuh: berpikir, merasa, dan bertindak.
Bisa jadi, tak satu pun dari mereka kelak jadi bupati, gubernur, atau seniman nasional. Tapi Laa Roiba telah menanam benihnya. Bahwa dari tanah kecil bernama Muaraenim, dari masjid yang sunyi di malam hari, lahir generasi yang tahu arah, dan berani mengambil peran.
TEKS : Tim Media PP Laa Roiba