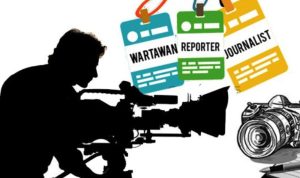Ada satu kisah yang selalu saya ingat ketika bicara tentang keteladanan Nabi Muhammad dalam keberagaman budaya. Waktu itu, Rasulullah SAW baru saja tiba di Madinah setelah hijrah. Apa yang pertama kali beliau lakukan?
Bukan membangun masjid dulu. Bukan pula membentuk “partai” atau mengatur jabatan. Tapi, beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, menata kehidupan plural masyarakat Madinah yang terdiri dari Muslim, Yahudi, dan kelompok lain. Dengan kata lain: Nabi mulai dengan membangun relasi sosial yang sehat. Nah, kalau ini tidak teladan, apa lagi?
Nabi Muhammad dan Madinah: Laboratorium Keberagaman
Madinah adalah laboratorium keberagaman budaya. Ada Yahudi Bani Nadhir, Bani Quraizhah, Bani Qainuqa’, ada Kristen Najran, ada kelompok pagan, dan tentu saja kaum Muslim yang datang dari Mekah. Semua itu adalah “Indonesia mini” pada masa Nabi. Di sini Nabi tidak membangun “benteng Islam” untuk menutup diri. Beliau malah membuat Piagam Madinah — kontrak sosial pertama yang mengatur hak dan kewajiban seluruh warga kota tanpa memandang agama.
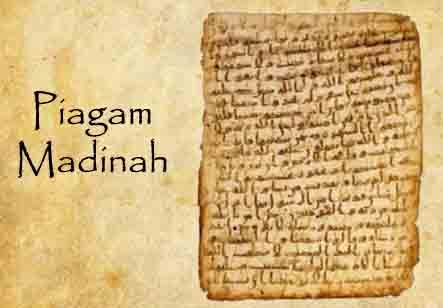
Piagam Madinah ini mengakui keberagaman sebagai realitas sosial. Tidak ada pemaksaan keyakinan, tidak ada monopoli kebenaran, yang ada hanyalah kesepakatan hidup berdampingan.
Dalam bahasa sekarang, Piagam Madinah adalah “konstitusi pluralisme”. Nabi membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil ‘alamin, bukan sekadar slogan di spanduk.
Bukan Menghancurkan, Tapi Mengubah Makna
Kalau kita cermati, Nabi Muhammad tidak datang untuk “menghancurkan” budaya Arab. Banyak tradisi Arab tetap berjalan, hanya dimurnikan niat dan arahnya.
Contoh paling mudah: haji. Sebelum Islam, ritual ini sudah ada di Mekah, tapi tercampur syirik. Nabi tidak menghancurkan Ka’bah, tapi membersihkan isinya dari berhala. Nabi tidak melarang orang tawaf, tapi mengubahnya menjadi ibadah tauhid.
Itu sebabnya, dalam setiap pertemuan antarbudaya, Nabi lebih suka transformasi ketimbang konfrontasi. Beliau tahu, budaya adalah kendaraan, bukan musuh. Yang penting adalah substansi nilai, bukan bungkusnya. Itulah yang kita sebut dakwah kultural: mendekati masyarakat dengan kebiasaan mereka, lalu mengisinya dengan nilai Islam, tanpa mematikan kreativitas lokal.
Dari Nabi ke Wali Songo: Konsistensi Dakwah Kultural
Model dakwah Nabi Muhammad itu nyambung dengan model Wali Songo di Nusantara. Sunan Kalijaga tidak marah pada wayang; beliau justru masuk lewat wayang, memberi makna baru pada cerita Mahabharata. Sunan Kudus tidak memaksa orang Jawa makan daging sapi di Idul Adha, menghargai sensitivitas Hindu. Sunan Bonang mengubah seni gamelan jadi media dzikir.
Semua wali itu paham, budaya lokal bukan ancaman, tetapi jembatan untuk mengantarkan nilai Islam. Inilah kearifan yang membuat Islam Indonesia terasa lembut, penuh warna, dan relatif damai dibandingkan daerah lain. Dakwah kultural ala Wali Songo adalah bukti bahwa Islam di Nusantara tumbuh bukan lewat pedang, tapi lewat seni, sastra, humor, dan persaudaraan.
Humor Nabi dan Humor Gus Dur
Saya sering berpikir, Gus Dur itu semacam “Wali Songo modern”. Caranya berdakwah santai, penuh humor, tapi dalem. Nabi Muhammad pun sering bercanda, asal tidak bohong. Gus Dur juga begitu: bercanda tentang politik, agama, dan budaya, tapi tujuannya menyadarkan.

Contohnya, Gus Dur pernah bilang, “Tuhan tidak perlu dibela, yang perlu dibela itu manusia.” Ini satire yang cerdas, karena sejatinya Nabi Muhammad pun begitu: beliau membela yang lemah, yang tertindas, yang dizalimi — bukan membela “agama” dalam arti simbolik.
Pelajaran untuk Indonesia: Mengelola Perbedaan
Indonesia ini miniatur Madinah. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu; ada Sunda, Jawa, Batak, Bugis, Dayak, Papua. Kalau kita tidak belajar dari Nabi dan Wali Songo, kita bisa jatuh ke konflik horizontal, saling curiga, saling menghakimi.
Padahal Al-Qur’an sudah jelas:
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)
Ayat ini menegaskan “lita’arafu” — supaya kita saling mengenal, bukan saling mengkafirkan. Nabi juga sudah mencontohkan hidup berdampingan dengan Yahudi Madinah, dengan Kristen Najran. Tapi mengapa kita di Indonesia malah suka saling “menyerang” sesama muslim hanya karena beda mazhab, beda organisasi, beda pilihan politik?
Alternatif Menghadapi Polarisasi
Kalau kita teladani Nabi, kita tidak akan mudah menghujat. Kita akan memilih jalan kultural: dialog, seni, pendekatan tradisi. Sama seperti Nabi yang tidak merobohkan Ka’bah, Wali Songo tidak merobohkan candi. Mereka tahu, memindahkan hati lebih penting daripada meruntuhkan bangunan.
Bayangkan kalau dakwah di Indonesia hari ini pakai pola itu. Bayangkan ormas Islam berlomba membuat pertunjukan budaya Islami, festival lintas agama, lomba pantun dakwah, atau majelis sholawat dengan irama Batanghari Sembilan khas Sumsel. Bukan hanya unik, tapi juga mendekatkan masyarakat pada Islam yang ramah, bukan marah.
Humor sebagai Jalan Tengah
Gus Dur pernah bilang, “Di Indonesia ini yang lebih penting itu menjaga kerukunan, bukan menghabiskan waktu mengurus orang sesat.” Satire ini dalam sekali. Nabi pun, kalau ada orang beda pendapat, beliau ajak dialog, bukan langsung dihabisi.
Humor dan seni adalah “soft power” Islam. Dengan itu kita bisa mengikis prasangka. Dengan itu pula kita bisa mengajarkan nilai Islam tanpa memaksa. Dakwah bukanlah arena untuk saling menjatuhkan, tapi ruang bersama untuk saling mengangkat.
Pelajaran Praktis untuk Kita
Dari keteladanan Nabi Muhammad, Wali Songo, dan Gus Dur, kita bisa menarik pelajaran praktis:
- Menghargai Tradisi Lokal: jangan buru-buru menuduh bid’ah; lihat substansi nilai.
- Menggunakan Media Seni: seperti sholawat, musik tradisional, pantun, wayang, untuk dakwah yang ramah.
- Dialog, Bukan Konfrontasi: selesaikan beda pandangan dengan komunikasi.
- Mendahulukan Substansi: akhlak, keadilan sosial, dan kemanusiaan lebih penting daripada simbol.
- Menjaga Humor dan Kesejukan: humor bisa melunakkan hati yang keras.
Dari Madinah ke Nusantara
Kalau Indonesia mau damai, maka jalan satu-satunya adalah jalan Nabi: membangun peradaban bersama, bukan menutup diri. Piagam Madinah jadi inspirasi kita untuk membuat “piagam Indonesia”: kesepakatan sosial yang menghormati agama dan budaya masing-masing.
Seperti Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah sesuai keyakinan mereka, kita pun harus membiarkan semua agama beribadah tanpa gangguan. Seperti Wali Songo mengangkat budaya Jawa, kita pun harus mengangkat budaya lokal: sholawat Sunda, rebana Melayu, musik Batanghari Sembilan Sumsel — semuanya bisa jadi media dakwah yang mempersatukan.
Nabi Muhammad, Wali Songo, dan Kita
Keteladanan Nabi Muhammad dalam keberagaman budaya bukan hanya sejarah, tapi peta jalan. Kita diajarkan untuk menghadapi perbedaan dengan seni, dialog, dan humor. Wali Songo sudah membuktikan metode ini di Nusantara. Gus Dur menghidupkannya kembali dalam konteks politik modern.
Sekarang giliran kita. Di tengah polarisasi politik, gesekan antaragama, atau bahkan antarmazhab, kita harus kembali ke akar: dakwah kultural. Islam bukan agama yang menakutkan, tapi agama yang penuh kasih. Nabi tidak menghapus budaya, tapi memberi ruh tauhid di dalamnya.

Kalau Nabi Muhammad saja yang maksum memilih jalan dialog dan budaya, siapa kita yang berani merasa lebih suci lalu menghujat yang lain?
Akhirnya, seperti kata Gus Dur:
“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Yang lebih penting dari kemanusiaan adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang kita kenal lewat kemanusiaan, bukan lewat kebencian.”
Itulah inti keteladanan Nabi Muhammad dalam keberagaman budaya: menghidupkan agama dengan cinta, bukan menghancurkan budaya dengan amarah.**
(Tulisan ini disarikan dari Kuliah Subuh di Masjid Nurul Hidayah, Komplek Tanah Putih PTBA Tanjung Enim, Ahad 14 September 2025)